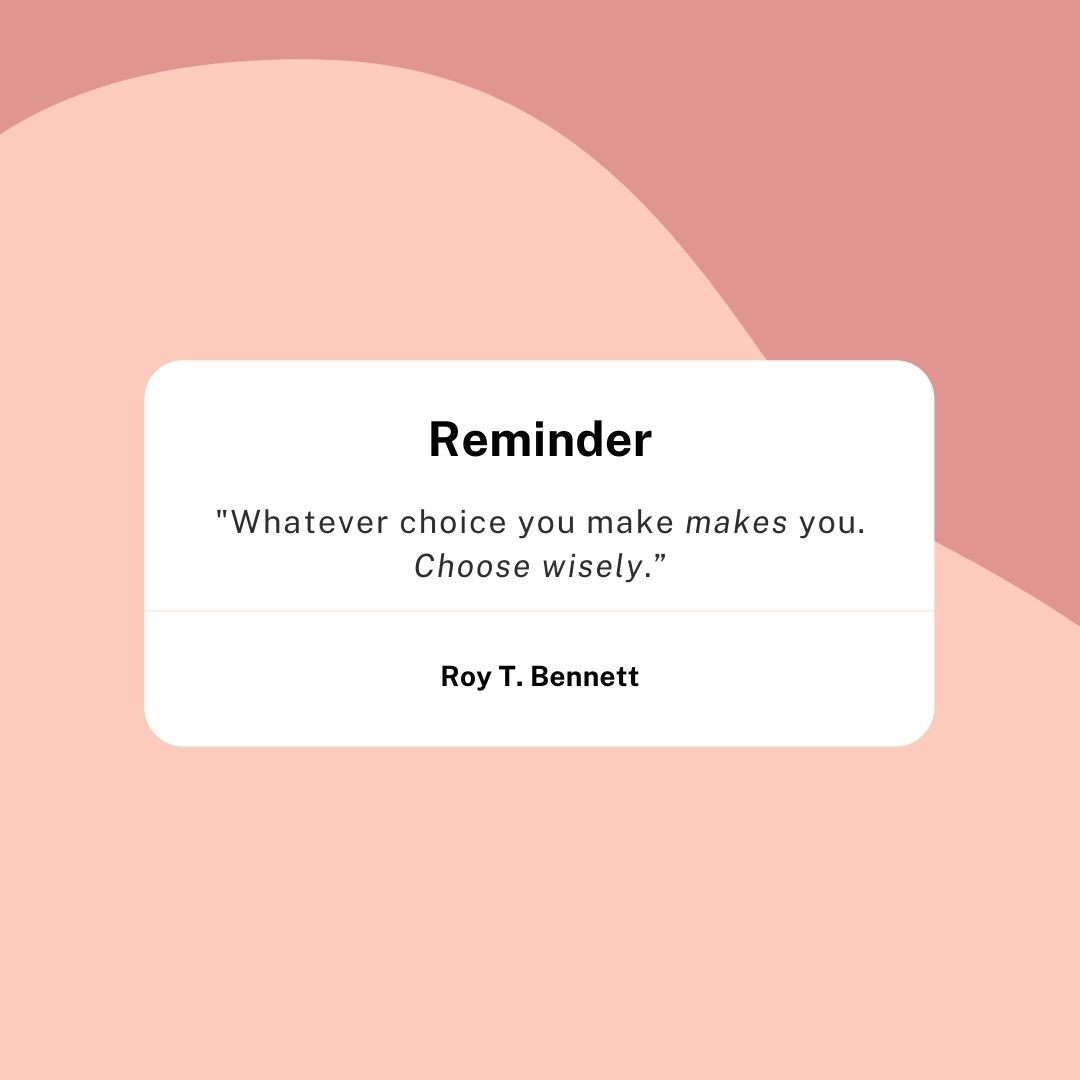Sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Mba Eno, yang beberapa waktu lalu mengadakan Paid Guest Post, sehingga memberikan aku kesempatan untuk menengok kembali sebuah tulisan lama di blog dan memutuskan untuk menambahkan beberapa pemikiran baru tentang hal tersebut. Selamat membaca, ya! 😊
***
Suatu hari, ketika aku masih bekerja sebagai barista di sebuah coffee shop berlogo putri duyung hijau, aku bersama atasanku—sebut saja dengan Mr. A—sedang mengerjakan laporan sales sambil mengobrol ringan. Obrolan berubah serius saat beliau melontarkan pertanyaan berikut:
“Kenapa ya, orang Tionghoa (di Indonesia) itu selalu menuruti apa yang orangtua mereka mau. Seperti pilihan jurusan kuliah harus yang “aman”, entah itu kedokteran, hukum atau bisnis. Soal pekerjaan pun begitu, mereka selalu diminta untuk melanjutkan usaha orangtuanya. Kayaknya mereka nggak punya pilihan dan impian sendiri, dan selamanya ‘ngumpet’ di bawah sayap orangtuanya”.
Fyi, aku adalah seorang keturunan Tionghoa generasi kedua, sementara Mr. A adalah orang lokal Bali.
Aku nggak yakin perkataan atasanku tersebut merupakan sebuah pertanyaan atau malah sebuah pernyataan. But I found it very interesting.
Btw, no hurt feeling dengan Mr. A, ya. He's one of the best leader I ever knew. He is a nice man. Disclaimer supaya nggak salah paham hihi
Oke, lanjut. Cerita sedikit dulu, ya, tentang pengalaman pribadi.
Aku dan adikku pernah ada di situasi "klise" seperti yang disebutkan Mr. A. Sejak SMA, aku ingin sekali masuk jurusan jurnalistik karena impianku menjadi seorang penulis dan kecintaanku pada majalah sejak usia remaja. Aku sampai pernah menulis postingan khusus (nggak usah dicari, ya! 😆) tentang khayalanku sebagai editor in chief di sebuah penerbitan majalah lokal ternama. Sementara, adik pertamaku sempat bercita-cita ingin masuk jurusan musik. But at the end, aku 'nyasar' di jurusan Sastra Mandarin dan adikku sekarang yang sudah menjadi dokter dan akan melanjutkan studinya kembali.
Jujur aja ya, aku sempat nggak berhenti mengutuk diri sendiri kenapa harus ‘terjebak’ dalam kondisi di mana harus menjalani jurusan yang sama sekali nggak pernah aku bayangkan. Aku nggak pernah ingin belajar sastra Mandarin, apalagi di negaranya langsung. Satu-satunya alasan mengapa akhirnya aku mengambil pilihan ini, karena tawaran beasiswa penuh selama empat tahun kuliah di China. Hampir nggak mungkin aku menolak tawaran tersebut karena di saat yang bersamaan, orangtua sedang struggle dalam finansial. Beasiswa tersebut amat sangat meringankan beban mereka, dibandingkan aku terus memaksa untuk berkuliah di universitas swasta Jakarta. (Cerita lengkapnya bisa dibaca di sini ya: What Brought Me to China 8 Years Ago)
Tahun pertama di universitas, hampir setiap hari aku mengeluh. Setiap bangun pagi, aku pasti menangis di kamar mandi sebelum masuk kelas. Entah apa yang ditangisi; antara homesick, kekesalan pribadi atau kondisi nyata gedung asrama kampus yang sangat berbeda dengan brosur yang kuterima (yak, ini nggak penting). Rutinitas itu terus berlanjut sampai sebulan lamanya. Capek nggak tuh, tiap mau ngampus, pake drama dulu. Penyesalan ini terus menganggu pikiran sehari-hari.
Terkadang aku lupa, bahwa aku berada di situasi tersebut karena pilihanku sendiri. Aku yang memutuskan sendiri untuk mengambil beasiswa ini dan menjalani semuanya selama empat tahun ke depan.
Di saat aku sadar bahwa semuanya ini adalah pilihanku sendiri, I started to gain a different perspective.
Meski orangtua yang memintaku untuk mengambil kesempatan kuliah di Guangzhou, mereka nggak pernah sekalipun melarangku melakukan hal-hal yang kusuka. Misalnya, menulis atau blogging. Mereka sangat mendukungku bahkan sampai detik ini. Ya gapapa deh nggak bisa kuliah jurnalistik. Setidaknya, berkat internet aku bisa menulis apapun yang aku mau dan ilmu juga tersebar luas di luar sana.
Ketika aku mulai mencoba membuka pikiran baru seperti itu, hari-hari kuliah terasa lebih menyenangkan. Berat, tapi setidaknya aku mulai happy. Dan aku pun mulai paham, bahwa keputusan apa pun yang aku pilih, aku harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihan tersebut.
“The man who complains about the way the ball bounces is likely to be the one who dropped it.”
-Lou Holtz
Saat kita melempar bola, hampir nggak mungkin rasanya kita protes tentang bagaimana bola tersebut memantul ke sana dan ke mari. It’s so silly. Gimanapun juga bola tersebut memantul demikian karena kita lah yang melemparnya seperti itu.
Hal yang sama ketika kita memilih sesuatu, kita juga lah yang harus bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Masa lo mau nyalahin orang lain? Iya, sih, orangtua yang minta gue kuliah ke China. Tapi toh akhirnya gue juga yang memutuskan untuk berangkat. If you need someone to blame on, it’s all on you.
*jleb jleb nusuk ke diri sendiri*
Kuncinya di sini adalah tanggung jawab.
Keputusan hidup apapun yang kita pilih, kita juga yang harus bisa bertanggung jawab dan berani terima segala risiko yang ada. Sama halnya ketika di antara kita yang mungkin punya privilege untuk kuliah sesuai minat pribadi atau bekerja di karir impian. Kasarnya, udah enak lo bisa nentuin pilihan sendiri, masa iya menjalaninya juga ogah-ogahan? 🤭
Beberapa waktu lalu, aku mengikuti sebuah parenting webinar bertemakan bakat dan potensi anak, yang mengundang Ernest Prakasa menjadi salah satu narasumber. Sebagai seorang yang juga keturunan Tionghoa, Ernest memaklumi hal-hal “klise” yang terjadi pada sebagian besar keluarga Tionghoa di Indonesia. Namun, ia berusaha untuk 'memutuskan' stigma masyarakat luas tentang etnis Tionghoa yang kayaknya hidupnya gitu-gitu aja, seperti anggapannya Mr. A. Ernest sempat bercerita, dia nggak pernah dituntut orangtuanya harus kuliah ini atau itu supaya karirnya bisa begini atau begitu. Ernest menjalani pilihanya sendiri dengan rasa tanggung jawab yang besar. Dia mampu meyakinkan orangtuanya bahwa apa pun yang dia jalani, dia akan bertanggung jawab sekalipun mungkin harus mengalami kegagalan. Menurut Ernest, saat kita menjalani pilihan sendiri, rasa tanggung jawab harusnya lebih besar ketimbang kita melakukan sesuatu demi orang lain. I can’t agree anymore about this statement.
Aku percaya setiap orangtua—lepas dari etnis apapun—ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Orangtua pasti punya harapan bahwa suatu hari anak-anak bisa menjadi sosok yang berguna dan diakui dalam masyarakat. Tapi kalau mau ngomongin spesifik orang Tionghoa (sekalian mengoreksi dikittt pernyataan Mr. A di atas), aku rasa penyebabnya karena kehidupan sulit di masa lalu. Yeye (sebutan untuk kakek dari pihak ayah) datang merantau dari China ke Indonesia untuk meneruskan hidup. Setelah menikah dan berkeluarga, Yeye harus menghidupi anak-anaknya, salah satunya, ya, papaku. Mereka yang tau sulitnya berjuang hidup di masa lalu, nggak ingin generasi berikutnya mengalami hal serupa. Itu kenapa orangtua Tionghoa ingin anak-anak punya masa depan yang pasti-pasti aja. Ngapain harus susah-susah dulu, kalau udah ada yang pasti. Begitulah kira-kira.
Terus, gimana dong untuk mereka yang udah jauh-jauh kuliah ke luar negeri, balik ke Indonesia ujung-ujungnya “jaga toko” orangtua?
To be honest, aku sempat berpikiran sempit seperti itu. Menilai keputusan hidup orang lain seenaknya. Sampai akhirnya aku pernah bekerja full time sebagai barista coffee shop dan suami yang sampai hari ini sukses meneruskan usaha orangtuanya sejak lulus kuliah, kemudian mendengar orang-orang di sekitar yang mengernyitkan dahi dan bertanya-tanya saat mengetahui pilihan hidup yang kami jalani:
“Itu si Jane jadi barista? Sayang banget sih S1 malah kerja jadi pelayan."
"Lah itu suami kamu jaga toko?"
"Ah jualan doang mah nggak usah sampai sarjana di luar negeri."
Lah, terus kenapa? Ada yang salah?
Mau jaga toko kek, mau jadi barista, mau jadi manager restoran, punya gelar sarjana atau nggak, kalau yang menjalaninya enjoy dan penuh tanggung jawab, kenapa harus dipermasalahkan? Kita nggak pernah bisa menghakimi hidup orang lain, karena kita nggak berada di ‘sepatu’ yang sama dengan mereka.
Percaya nggak, sih, orangtua itu hanya ingin melihat anak-anaknya bahagia?
Kalau kita bisa bahagia dengan melakukan apapun itu yang kita lakukan sekarang ini, orangtua pun pasti ikut bangga kok.
Jadi, apakah seorang Jane bahagia dengan hidupnya sekarang ini?
Puji Tuhan, aku sangat bahagia menjalani hidup saat ini. I'm not saying that my life is easy. Semakin lama kita hidup di dunia ini, semakin berat juga kehidupan yang dijalani. Maka dari itu, aku mencoba untuk bisa memilih keputusan dengan bijak, supaya aku nggak terus-terusan menyesali apa yang di belakang, namun fokus menjalani yang terbaik untuk di masa depan. Lagipula, kalau sebelas tahun yang lalu aku nggak berangkat ke Guangzhou, nggak ketemu calon suami dong? 🙈
Sementara soal adikku, kalau kalian penasaran, so far dia sangat mencintai pekerjaannya sebagai dokter. Dia berkesempatan tinggal di beberapa kota di Indonesia dan membantu banyak orang yang membutuhkan.
Mau kamu jadi dokter, guru, pengacara, entrepreneur, presiden, menteri, jualan online, barista atau ibu rumah tangga sekalipun (yes, I’m talking about myself, again, here :P), as long as you’re happy and being responsible while doing it, you’re just fine. Your life doesn’t depend on what people say about you.
As for myself, I want to always make my parents proud while doing things that I love. Malahan aku sangat berterima kasih karena mereka sudah melihat potensi dalam diriku dan dua adikku lainnya, nggak menyerah untuk terus mendorong kami, sehingga kami bertiga mampu menjalani kehidupan sampai saat ini (:
Sebagai penutup, aku ingin memberikan salah satu kutipan favorit tentang pilihan hidup. Semoga keputusan apapun yang kita ambil hari ini, jangan pernah disesali. Sebaliknya, biarlah semuanya bisa menjadi pembelajaran hidup berharga di kemudian hari 💜
"In the long run, we shape our lives, and we shape ourselves. The process never ends until we die. And the choices we make are ultimately our own responsibility."
-Eleanor Roosevelt